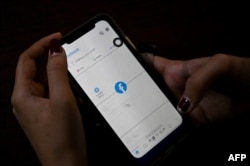Menurut Indeks Represi Digital, Indonesia memiliki situasi lebih baik dibanding sejumlah tetangga dalam kebebasan di dunia internet. Namun, meski demikian situasi riil yang terjadi di Tanah Air diangggap mengkhawatirkan, dan butuh upaya ekstra untuk menjamin kebebasan berekspresi.
Penilaian itu disampaikan peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Diah Kusumaningrum, setelah melakukan kajian terhadap riset sejumlah peneliti. Empat negara yang menjadi obyek kajian adalah Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam.
“Kalau dilihat dari skor yang ada, sebenarnya Indonesia agak jauh ya dari mereka. Masih jauh lebih terbuka dibandingkan empat negara tersebut, tetapi saya kira ini bukan alasan untuk complaisant,” kata Diah, Jumat (30/9).
Diah memaparkan kajiannya dalam diskusi Represi Digital dengan Dalih “Melawan Hoaks”: Pengalaman Empat Negara ASEAN”. Diskusi ini diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Paramadina bekerja sama dengan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.
Indonesia memang cukup baik dalam indek represi digital. Namun, ada sejumlah kasus di dalam negeri, yang membuat sejumlah pihak menilai ada potensi pengekangan cukup kuat berdasar aturan hukum yang ada, terutama dengan berlakunya UU ITE.
Diah menegaskan, dengan skor yang sebenarnya cukup baik dalam indeks represi digital, banyak pihak di Indonesia merasa represi digital di Indonesia cukup terasa.
“Itu rasanya sudah segitu menggerahkan, sebegitu mencekik. Bayangkan kalau nanti sampai ke tingkat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Kamboja, Myanmar Thailand dan Vietnam. Kalau tidak dihadang dari sekarang, itu akan jauh lebih susah nanti hidup kita dan perlawanan kita,” tegasnya.
Secara rinci, Diah memaparkan bahwa di Kamboja, konten digital yang diberi label sebagai hoaks atau berita bohong adalah yang dianggap membahayakan keamanan nasional, kesehatan keselamatan dan keuangan publik, dan hubungan diplomatik. Bisa juga dinilai membahayakan hasil pemilu nasional, kohesi sosial, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan lembaga negara.
Sedangkan di Myanmar, label hoaks disematkan pada informasi, cuitan, foto dan sejenisnya yang dianggap mengancam keamanan nasional, mendisrupsi supremasi militer atau menghina pejabat pemerintahan, serta menyabotase hubungan luar negeri.
Sementara di Thailand, hoaks dikenakan pada konten yang menimbulkan kepanikan publik, mengganggu keselamatan perekonomian dan infrastruktur publik, mendorong perpecahan nasional, membahayakan reputasi tradisi dan lembaga negara khususnya monarki. Di Vietnam, label diberikan jika mencerminkan oposisi terhadap negara, mengancam keamanan nasional, ketertiban umum dan keselamatan. Ada aturan khusus di masa pandemi, hoaks juga diberikan kepada berita yang dianggap menyebarkan ketakutan seputar pandemi, dan mendorong warga melakukan hal-hal yang ujungnya merugikan negara.
Enam Bentuk Represi
Berbicara dalam diskusi yang sama, Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet mencatat setidaknya enam bentuk represi digital di Indonesia.
“Pertama adalah ada cap hoaks yang setiap kali muncul dari pemerintah. Yang kedua ada upaya pemidanaan atau disidang dan dipenjara. yang ketiga ada pemutusan internet atau diputus akses internetnya. Yang keempat adalah ditertibkan oleh polisi. Yang kelima, ditanam bukti palsu lewat peretasan, dan yang keenam ada perintah penghapusan ke platform,” bebernya.
Dalam konteks cap hoaks yang diterapkan pemerintah, Damar menguraikan sudah cukup lama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyematkan segmen tertentu di dalam lamannya, di mana cap hoask diberikan.
“Dan yang menarik adalah, ada hoaks yang dicap oleh pemerintah, dan kita tahu itu tidak benar,” tambahnya.
Damar memberi contoh, cap hoaks yang tidak tepat adalah terhadap postingan aktivis pembela Papua, Veronica Koman, tentang dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.
“Dan kita tahu, tidak lama kemudian Kominfo meminta maaf karena dia keliru dalam melakukan pencapan hoaks ini. Tetapi dampak dari cap tersebut, sangat panjang dan saya rasa itu awal persoalan pemadaman internet di Papua,” ujarnya lagi.
Damar juga menyebut, cap hoaks keliru diberikan terhadap laporan jurnalistik dari Project Multatuli, yang mengangkat kasus kekerasan seksual yang tidak diproses oleh Polres Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Cap hoaks ini, diberikan sendiri oleh Humas Polres Luwu Timur, dengan menyatakan laporan Project Multatuli itu tidak benar.
“Tidak lupa saya harus mengatakan contoh-contoh lain, misalnya cap hoaks pada berita di Republika, lalu juga ada cap hoaks pada Wadas melawan, saat kelompok petani di Jawa Tengah menyampaikan adanya upaya intimidasi petani, yang diperiksa oleh polisi di sana,” tambah Damar.
Buruknya kemudian, cap hoaks tidak hanya datang dari Kominfo, tetapi bisa dilakukan oleh hampir seluruh lembaga pemerintah. Perlu upaya lebih dari masyarakat sipil, untuk menetang tindakan semacam ini ke depan.
“Misalnya pada kasus Veronica Koman itu didorong oleh teman-teman Aliansi Jurnalis Independen. Lalu pada laporan teman-teman Project Multatuli, yang bersuara adalah Komite Keselamatan Jurnalis,” tandasnya.
Kesulitan Pengaturan
Pada bagian lain, Shita Laksmi, Direktur Eksekutif Tifa Foundation menyebut sesuai aturan yang berlaku, terdapat sejumlah tindakan yang bisa dijerat hukum.
“Ada konten melanggar hukum dengan beragam macam definisi, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan atau ancaman, penyebaran informasi bohong atau misinformasi,” detilnya.
“ Ada juga hasutan kebencian berbasis SARA, penghinaan presiden dan pejabat publik terkait dengan COVID-19, penyebaran informasi salah terkait COVID-19, dan perlindungan dan keamanan data pribadi,” tambahnya.
Sedangkan sanksi yang diberikan pemerintah Indonesia juga cukup beragam. Mulai dari denda, hukuman penjara, pemblokiran konten melalui ISP, permintaan untuk menurunkan konten di website, dan penutupan website.
Dunia digital sendiri, secara umum masih memiliki sejumlah persoalan karena ini merupakan sektor lintas negara.
“Persoalannya adalah, kalau yang non-lintas negara, kan gampang, satu undang-undang maka selesai. Ini persoalannya adalah, banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja antar negara dengan pengaturan sendiri-sendiri. Rata-rata mereka patuh pada community guideline mereka sendiri, tetapi mereka tidak patuh terhadap peraturan di negara dimana mereka beroperasi,” ujarnya.
Kenyataan ini, membuat negara-negara yang tidak demokratis kebingungan, karena mereka kesulitan menerapkan regulasi untuk platform lintas negara. [ns/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.